Relawan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku tidak gentar dengan maraknya praktik politik uang menjelang Pilpres 2024. Dukungan kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak bakal surut.
Salah satunya, Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI). Relawan yang dikomandoi Syarief Hidayatullah itu mengakui, jagoannya memang tidak punya banyak modal keuangan untuk maju di pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 (rm.id, 2/1/2022).
Menurutnya, Anies punya modal alami saja, yakni prestasi dan rekam jejaknya sebagai birokrat dan akademisi. Publik juga melihat rekam jejak prestasi, integritas, dan keberpihakan Anies kepada masyarakat bawah.
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, menempatkan nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada posisi pertama sebagai calon presiden yang diperkirakan akan menarik suara publik terbanyak dalam Pilpres 2024 (voi, 26/3/2021).
Apalagi, lanjutnya, Anies di mata dunia saat ini terlihat banyak prestasi. Terutama, bisa mengembalikan Jakarta tidak masuk dalam 10 besar kota termacet dan menjadikannya kota yang tertata dengan rapi di dunia.
Namun, ada tiga jalan terjal yang mesti dilalui oleh Anies. Pertama, mulai tahun ini Anies tidak lagi menjabat sebagai gubernur. Artinya, bukan perkara mudah baginya untuk merawat elektabilitasnya sebab akan menganggur secara politik.
Kedua, status Anies yang bukan kader partai (calon independen). Anies bakal kesulitan mencari dukungan politik di tengah situasi para ketua umum dan elite parpol juga tengah berambisi maju untuk mendapatkan coattail effect (efek ekor jas).
Teori coattail effect menjelaskan pengaruh kekuatan elektoral seorang calon presiden dan partai yang mengusungnya. Artinya, seorang calon presiden atau presiden yang populer dengan tingkat elektabilitas yang tinggi akan memberikan keuntungan positif secara elektoral kepada partai yang mengusungnya sebagai calon.
Situasi itu, bakal lebih sulit lantaran Anies tidak memiliki logistik yang besar. Sejauh ini, satu-satunya parpol yang secara terang-benderang mendukung Anies hanya PKS. Sikap politik itu, menurutnya justru aneh lantaran PKS merupakan partai kader dan saat ini memiliki sejumlah kandidat potensial.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, 92 persen calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi Pilkada dibiayai oleh cukong atau pengusaha pemilik perusahaan besar di Indonesia (cnnindonesia.com, 11/9/2020).
Dampaknya, kepala daerah yang terpilih itu harus melakukan balas jasa dengan memberikan kebijakan yang menguntungkan bagi para cukong tersebut yang melahirkan korupsi kebijakan. Demikian pula yang terjadi pada Pilpres yang bahkan membutuhkan modal jumbo, estimasi modal calon presiden berada dikisaran Rp8 sampai Rp15 triliun.
Ketiga, yang mesti dilalui Anies adalah banyaknya kompetitor yang juga muncul. Seperti, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Kondisi di atas makin menantang karena sistem pemilihan dalam demokrasi mutlak membutuhkan logistik tak terbatas. Demokrasi yang mengandalkan votes (suara) dengan mudah diubah menjadi sebuah komoditas politik yang diperjual-belikan.
Suburnya praktik politik uang (money politics) itu juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi di level akar rumput yang tumbuh subur.
Karena dianggap suatu kewajaran, masyarakat tidak peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya karena sesuatu yang menguntungkan (simbiosis mutualisme). Politik uang terjadi karena kuatnya persepsi bahwa pemilu dan pilkada sebagai perayaan demokrasi, sehingga memunculkan budaya pragmatisme. Padahal, politik uang dapat melanggengkan korupsi politik.
Robin Hodess dalam Introduction to Global Corruption Report (2004), mendefinisikan korupsi politik sebagai penyelewengan kekuasaan yang dilakukan politisi (political leaders or elected officials) untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan tujuan meningkatkan kekuasaan atau kekayaan.
Korupsi oleh pemegang kekuasaan atau kewenangan politik ini tidak hanya terjadi dalam bentuk transaksi uang, tetapi juga pengaruh (trading in influence). Dari sisi waktu, korupsi politik dapat terjadi sebelum, saat, dan setelah pelaku menjadi pejabat publik.
Politik uang pada Pemilu 2019 misalnya, tidak kalah masif dibanding pada 2014. Apalagi, Pemilu 2019 lebih kompetitif, karena ambang batas parlemen (parliamentary threshold) naik dari 3,5 persen menjadi 4 persen. Bisa dibayangkan Pemilu 2024 dengan ambang batas yang mencapai 20 persen, akan menguatkan politik uang.
Mengutip survei nasional pasca Pileg 2014 dengan hasil penelitian Doktoral, Burhanuddin Muhtadi menemukan fakta bahwa satu di antara tiga orang pemilih di Indonesia terpapar praktik politik uang. Ini menunjukkan buramnya sistem demokrasi. Malapraktik elektoral terjadi pada semua level pemilihan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat politik uang terbesar ketiga di dunia (rentang waktu survei antara 2000-2014).
Ada dua hal yang perlu segera dibenahi. Pertama, proses rekrutmen dan pendanaan partai politik. Kedua, pendidikan politik bagi pemilih. Namun pertanyaanya adalah apakah membenahi kedua poin tersebut, dapat mencabut akar persoalan politik uang?
Berangkat dari dua hal tersebut, minimal terdapat lima sumber pengeluaran yang menyebabkan tingginya ongkos politik. Pertama biaya pencalonan (ongkos perahu politik) yang lumrah disebut sebagai “mahar politik”. Kedua, biaya kampanye yang meliputi atribut kampanye, Tim pemenangan, serta penggunaan media elektronik dan cetak.
Ketiga, ongkos konsultasi politik dan survei. Keempat, politik uang yang masih marak dilakukan, termasuk “serangan fajar”, dan sumbangan ke kantong pemilih. Kelima, biaya yang besar adalah perihal keberadaan saksi pada hari perhitungan suara.
Persoalan mahar politik merupakan salah satu yang membuat proses pencalonan membutuhkan waktu yang cukup lama, banyak partai yang mengambil injury time untuk mendaftar ke KPU yang sebenarnya menyiratkan adanya tarik menarik seberapa besar “mahar” yang dikeluarkan.
Termasuk calon yang batal dicalonkan di detik-detik terakhir. Hal ini menjadi momentum yang penting untuk melihat bahwa ada persoalan serius dalam mekanisme Pemilu yang membuat bargaining position politik menguat yang ujungnya melahirkan perilaku koruptif.
Direktur Eksekutif Indonesia Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi menyebut bahwa maraknya praktik jual beli dukungan kepada pasangan calon untuk pendanaan partai politik menghadapi Pemilu tahun 2019 (beritasatu.com, 17/1/2018).
Hanafi memprediksi anggaran yang dibutuhkan parpol untuk pemilihan legislatif 2019 saja adalah Rp81 triliun dan untuk Pemilihan Presiden sebesar Rp100 triliun. Artinya, Parpol bakal habis-habisan di Pemilu berikutnya untuk memenangkan Pileg dan Pilpres.
Demikianlah implementasi demokrasi menunjukkan penghambur-hamburan uang dan menyuburkan perilaku koruptif. Pemilu sebagai mekanisme perwujudan partisipasi masyarakat baik dalam pemilihan presiden dan pemilihan wakil rakyat adalah pemborosan uang untuk apa yang dinamakan ‘partisipasi’.
Menurut catatan Nielsen, belanja iklan pada Pemilu 2014 saja mencapai Rp2,134 triliun. Jumlah biaya iklan politik yang realistis sulit diketahui karena banyak iklan terselubung. Adapun biaya Pilpres yang dikeluarkan melalui APBN ada di kisaran Rp26,9 triliun.
Gambaran pemilihan dalam sistem demokrasi menunjukkan bahwa politik uang bukan hanya soal pragmatisme elit politik, namun juga sebagai konsekuensi logis dari demokrasi yang hanya bisa tegak ketika ditopang oleh investor politik atau para pemodal.
Realitas di atas bertentangan dengan mekanisme pemilihan dalam Islam yang kedaulatannya ada di tangan syara’. Pemilihan Khalifah dilaksanakan secara transparan, akurat, akuntabel, dan berlangsung singkat. Sehingga, lebih efisien dan tidak memerlukan politik uang. Seorang Khalifah terbuka untuk dikoreksi oleh rakyatnya. Sebagaimana pidato Khalifah Abu Bakar ra.
Di antara penggalan pidatonya adalah ia mengatakan, “Sungguh kalian membaiat aku, sedangkan aku bukan orang terbaik di antara kalian. Karena itu bila kalian mendapati aku berada di jalan kebaikan, maka bantulah aku. Sebaliknya, bila aku berada di atas jalan yang salah, maka luruskanlah aku. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, bila aku melanggar, janganlah kalian menaati aku…” (Al-Bidâyah, 5/248).
Khalifah Abu Bakar ra., sangat menyadari bahwa ada satu misi utama yang harus dia emban, yakni pelaksanaan syariat Islam sebagai wujud nyata dari ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah Abu Bakar ra., mengingatkan orang-orang yang hadir ketika itu untuk menaati dirinya sepanjang ia menaati syariat Allah.
Dari sini menjadi sangat jelas bahwa pertanggungjawaban jabatan nantinya di akhirat terkait dengan tiga hal. Pertama, apakah jabatan itu diemban untuk melaksanakan ketaatan pada Allah Swt. atau bukan? Kedua, bagaimana jabatan itu diperoleh? Ketiga, apakah dilaksanakan dengan amanah atau justru untuk berbuat kecurangan? Wallahu’alam bishawab.
Oleh : Rabihah Pananrangi

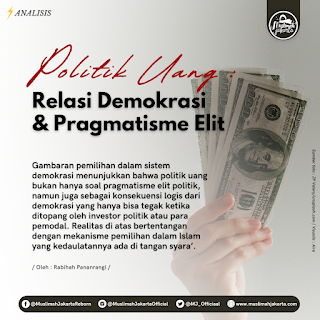



0 Komentar